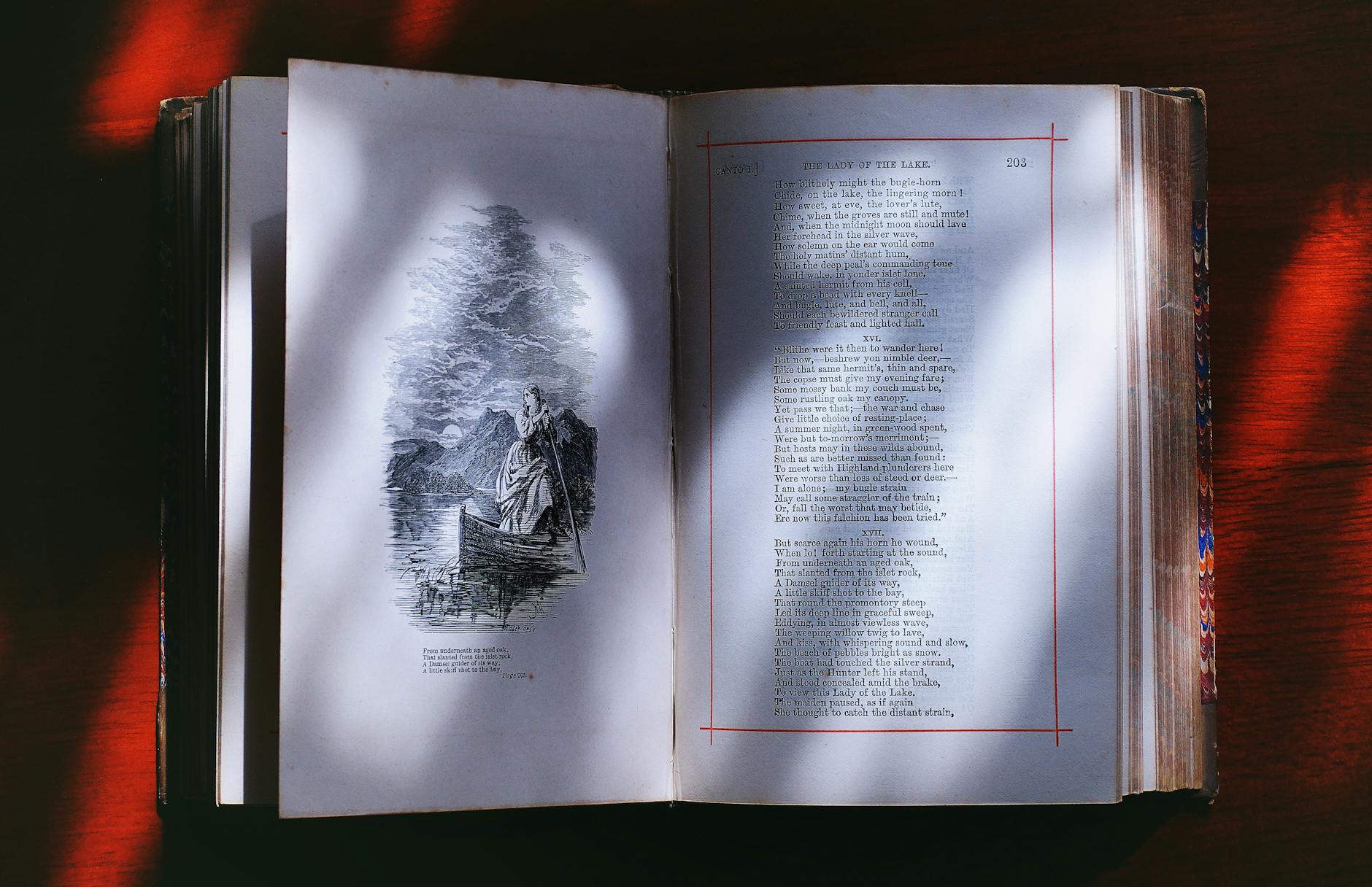
Iseng saya telepon seorang sahabat yang kini tinggal di daerah asalnya. Sebelumnya ia sudah bekerja dan mengais rupiah di Jakarta sebagai penulis wara (copywriter). Dulu ia berkelana ke mana-mana. Ditraktir perusahaan dan klien menginap di hotel, menghadiri acara-acara elit, dengan kenyamanan dan logistik yang melimpah ruah. Bisa tidur nyenyak dan makan kenyang tanpa mengeluarkan sepeserpun dari rekening sendiri.
Kini roda takdir berbalik radikal. Ia diputus hubungan kerja oleh perusahaan tempatnya bekerja tanpa ada pilihan. Usianya sudah mendekati kepala enam dan tiada ijazah sarjana. Otomatis ia terdepak di era AI dan tenaga kerja muda yang murah meriah. Meski gajinya juga secuil selisihnya dari UMR Jakarta. Kalau istilah sekarang, ia melakukan ‘job hugging‘. Tak suka dengan budaya kerja perusahaan, tak suka dengan pilihan politik pemilik perusahaan, punya cara pandang dan sikap politik berbeda tapi toh demikian ia bertahan selama yang ia bisa demi perut. Ia masih menanggung satu orang anak dan istri dan saudara ipar yang lemah mental.
Kini teman saya dipaksa keadaan untuk membuka warung di rumah. Warung jajanan anak, menyewakan wifi secara harian untuk anak-anak dan remaja yang sedang nge-push rank online games, dan berjualan ayam potong. Untuk yang terakhir, ia mesti bangun subuh, bersepeda ke kampung tetangga tempat rumah jagal berada dan memotong ayam utuh menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil untuk dijual eceran. Sebelumnya jari-jarinya yang kering dan kapalan karena benturan ke papan ketik laptop, sekarang basah dan amis kena daging ayam segar yang berlumuran darah. Tak masalah karena toh masih halal kan?
Di sela kesibukannya itu, ia ternyata masih membuka diri untuk pekerjaan yang berbau literasi. Baru-baru ini ia ditawari pekerjaan menyunting sebuah buku yang ditulis tokoh petinggi negara. Saya bertaruh, itu juga bukan si petinggi sendiri yang menulis. Paling juga ajudan atau jongosnya, atau suruhan jongosnya. Ya apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang di zaman sekarang? Atau mungkin saja ditulis pakai AI. Entahlah.
Dengan beban pekerjaan menyunting draft buku itu, ia diberi ganjaran dua juta rupiah saja. Saya terkekeh, “Harusnya lebih tuh!” Bukan untuk menyakiti hati teman saya tapi semata karena kesal dengan kondisi yang makin mengenaskan bagi seluruh pekerja jurnalistik dan pekerja kata. Inflasi keahlian dan keterampilan kaum seperti kami sangat tajam menukik ke bawah. Sedih.
Saya bertanya apa isi draft itu. Isinya ternyata menyanjung-nyanjung langkah pemerintah sekarang: dari intensifikasi penanaman kelapa sawit demi ambisi swasembada biofuel, sampai tambang-tambang ekstraksi mineral dan logam demi kemajuan ekonomi bangsa. Jujur ia makan hati sambil mengerjakan penyuntingannya. Teman saya suka menanam dan cinta lingkungan dan pepohonan dan hutan. Saya paham konflik moral yang ia alami.
Tapi itulah yang menjadi dilema kami kaum idealis miskin. Kami tidak pragmatis dan oportunis dalam hidup. Akibatnya kami harus hidup dalam belas kasihan penguasa dan pemilik modal yang cara pikir dan perilakunya jauh dari standar moralitas ideal kami.
Bisakah kaum idealis jadi kaya raya dan terlepas dari ketergantungan kaum kapitalistik? Susah karena dunia ini dicengkeram sistem kapitalisme yang mengakar sejak lama yang bermula dari pendirian VOC di Belanda. Dan anehnya Indonesia jadi salah satu pemicu utama berdirinya kapitalisme dengan adanya kutukan yang tersamar sebagai berkah yang bernama rempah-rempah. (*/)

Leave a Reply to Ester Pandiangan Cancel reply